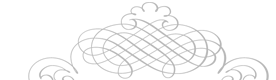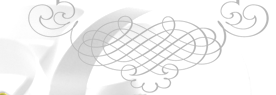Salman Al Farisi memang sudah waktunya
menikah. Seorang wanita Anshar yang dikenalnya sebagai wanita mukminah
lagi shalihah juga telah mengambil tempat di hatinya. Tentu saja bukan
sebagai kekasih. Tetapi sebagai sebuah pilihan dan pilahan yang dirasa
tepat. Pilihan menurut akal sehat. Dan pilahan menurut perasaan yang
halus, juga ruh yang suci.
Tapi bagaimanapun, ia merasa asing di
sini. Madinah bukanlah tempat kelahirannya. Madinah bukanlah tempatnya
tumbuh dewasa. Madinah memiliki adat, rasa bahasa, dan rupa-rupa yang
belum begitu dikenalnya. Ia berfikir, melamar seorang gadis pribumi
tentu menjadi sebuah urusan yang pelik bagi seorang pendatang. Harus ada
seorang yang akrab dengan tradisi Madinah berbicara untuknya dalam
khithbah. Maka disampaikannyalah gelegak hati itu kepada shahabat Anshar
yang dipersaudarakan dengannya, Abu Darda’.
”Subhanallaah.. wal hamdulillaah..”,
girang Abu Darda’ mendengarnya. Mereka tersenyum bahagia dan berpelukan.
Maka setelah persiapan dirasa cukup, beriringanlah kedua shahabat itu
menuju sebuah rumah di penjuru tengah kota Madinah. Rumah dari seorang
wanita yang shalihah lagi bertaqwa.
”Saya adalah Abu Darda’, dan ini adalah
saudara saya Salman seorang Persia. Allah telah memuliakannya dengan
Islam dan dia juga telah memuliakan Islam dengan amal dan jihadnya. Dia
memiliki kedudukan yang utama di sisi Rasulullah Shallallaahu ’Alaihi wa
Sallam, sampai-sampai beliau menyebutnya sebagai ahli bait-nya. Saya
datang untuk mewakili saudara saya ini melamar putri Anda untuk
dipersuntingnya.”, fasih Abud Darda’ bicara dalam logat Bani Najjar yang
paling murni.
”Adalah kehormatan bagi kami”, ucap tuan
rumah, ”Menerima Anda berdua, shahabat Rasulullah yang mulia. Dan
adalah kehormatan bagi keluarga ini bermenantukan seorang shahabat
Rasulullah yang utama. Akan tetapi hak jawab ini sepenuhnya saya
serahkan pada puteri kami.” Tuan rumah memberi isyarat ke arah hijab
yang di belakangnya sang puteri menanti dengan segala debar hati.
”Maafkan kami atas keterusterangan ini”,
kata suara lembut itu. Ternyata sang ibu yang bicara mewakili
puterinya. ”Tetapi karena Anda berdua yang datang, maka dengan mengharap
ridha Allah saya menjawab bahwa puteri kami menolak pinangan Salman.
Namun jika Abu Darda’ kemudian juga memiliki urusan yang sama, maka
puteri kami telah menyiapkan jawaban mengiyakan.”
Jelas sudah. Keterusterangan yang
mengejutkan, ironis, sekaligus indah. Sang puteri lebih tertarik kepada
pengantar daripada pelamarnya! Itu mengejutkan dan ironis. Tapi saya
juga mengatakan indah karena satu alasan; reaksi Salman. Bayangkan
sebuah perasaan, di mana cinta dan persaudaraan bergejolak berebut
tempat dalam hati. Bayangkan sebentuk malu yang membuncah dan bertemu
dengan gelombang kesadaran; bahwa dia memang belum punya hak apapun atas
orang yang dicintainya. Mari kita dengar ia bicara.
”Allahu Akbar!”, seru Salman, ”Semua
mahar dan nafkah yang kupersiapkan ini akan aku serahkan pada Abu
Darda’, dan aku akan menjadi saksi pernikahan kalian!”
Cinta tak harus memiliki. Dan sejatinya
kita memang tak pernah memiliki apapun dalam kehidupan ini. Salman
mengajarkan kita untuk meraih kesadaran tinggi itu di tengah perasaan
yang berkecamuk rumit; malu, kecewa, sedih, merasa salah memilih
pengantar –untuk tidak mengatakan ’merasa dikhianati’-, merasa berada di
tempat yang keliru, di negeri yang salah, dan seterusnya. Ini tak
mudah. Dan kita yang sering merasa memiliki orang yang kita cintai, mari
belajar pada Salman. Tentang sebuah kesadaran yang kadang harus kita
munculkan dalam situasi yang tak mudah.
Sergapan rasa memiliki terkadang sangat
memabukkan.. Rasa memiliki seringkali membawa kelalaian. Kata orang
Jawa, ”Milik nggendhong lali”. Maka menjadi seorang manusia yang
hakikatnya hamba adalah belajar untuk menikmati sesuatu yang bukan milik
kita, sekaligus mempertahankan kesadaran bahwa kita hanya dipinjami.
Inilah sulitnya. Tak seperti seorang tukang parkir yang hanya dititipi,
kita diberi bekal oleh Allah untuk mengayakan nilai guna karuniaNya.
Maka rasa memiliki kadang menjadi sulit ditepis.
|